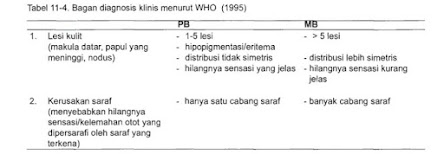KUSTA
PENDAHULUAN
Kusta termasuk penyakit tertua. Kata kusta berasal dari bahasa India kustha, dikenal sejak 1400 tahun sebelum Masehi. Kata kusta disebut dalam kitab lnjil, terjemahan dari bahasa Hebrew zaraath, yang sebenarnya mencakup beberapa penyakit kulit lainnya. Ternyata bahwa pelbagai deskripsi mengenai penyakit ini sangat kabur, apabila dibandingkan dengan kusta yang kita kenal sekarang.
DEFINISI
Kusta merupakan penyakit infeksi yang kronik, dan penyebabnya ialah Mycobacterium leprae yang bersifat intraselular obligat. Saraf perifer sebagai afinitas pertama, lalu kulit dan mukosa traktus respiratorius bagian atas, kemudian dapat ke organ lain kecuali susunan saraf pusat.
SINONIM
Lepra, morbus Hansen (MH)
EPIDEMIOLOGI
Masalah epidermiologi masih belum terpecah- kan, cara penularan belum diketahui pasti hanya berdasarkan anggapan klasik yaitu melalui kontak langsung antar kulit yang lama dan erat. Anggapan kedua ialah secara inhalasi, sebab M. leprae masih dapat hidup beberapa hari dalam droplet.
Masa tunas sangat bervariasi, antara 40 hari sampai 40 tahun, umumnya beberapa tahun, rata- rata 3-5 tahun.
Penyebaran penyakit kusta dari suatu tempat ke tempat lain sampai tersebar di seluruh dunia, tampaknya disebabkan oleh perpindahan penduduk yang terinfeksi penyakit tersebut. Masuknya kusta ke pulau-pulau Melanesia termasuk Indonesia,
diperkirakan terbawa oleh orang-orang Cina . Distribusi penyakit tiap-tiap negara maupun di dalam satu negara sendiri temyata berbeda-beda. Demikian pula penyebab penyakit kusta menurun atau menghilang pada suatu negara sampai saat ini belum jelas benar.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah patogenesis kuman penyebab, cara penu- laran, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan, varian genetik yang berhubungan dengan kerentan- an, perubahan imunitas, dan kemungkinan adanya reservoir diluar manusia. Penyakit kusta masa kini berbeda dengan kusta masa dulu, tetapi meskipun demikian masih banyak hal-hal yang belum jelas diketahui, sehingga masih merupakan tantangan yang luas bagi para ilmuwan untuk pemecahannya.
Belum ditemukan medium artifisial , mem- persulit dalam mempelajari sifat-sifat M. leprae . Sebagai sumber infeksi hanyalah manusia, meski- pun masih dipikirkan adanya kemungkinan di luar manusia. Penderita yang mengandung M. leprae jauh lebih banyak (sampai 1013 per gram jaringan), dibandingkan dengan penderita yang mengandung 107 , daya penularannya hanya tiga sampai sepuluh kali lebih besar.
Kusta bukan penyakit keturunan . Kuman dapat ditemukan di kulit, folikel rambut, kelenjar keringat, dan air susu ibu, jarang didapat dalam urin. Sputum dapat banyak nengandung M. /eprae yang berasal dari traktus respiratorius atas . T empat implantasi tidak selalu menjadi tempat lesi pertama. Dapat menyerang semua umur, anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa. Di Indonesia penderita anak-anak di bawah umur 14 tahun didapatkan ± 13 %, tetapi anak di bawah umur 1 tahun jarang sekali. Saat ini usaha pencatatan penderita di bawah usia 1 tahun penting dilakukan untuk dicari kemungkinan ada tidaknya kusta kongenital. Frekuensi tertinggi terdapat pada kelompok umur antara 25-35 tahun.
Kusta terdapat di seluruh dunia , terutama di Asia, Afrika, Amerika Latin, daerah tropis dan subtropis , serta masyarakat yang sosial ekonomi- nya rendah . Makin rendah sosial ekonomi makin berat penyakitnya, sebaliknya faktor sosial eko- nomi tinggi sangat membantu penyembuhan . Didapatkan variasi reaksi terhadap infeksi M. /eprae yang mengakibatkan variasi gambaran klinis (spektrum dan lain-lain) di pelbagai suku bangsa. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor genetik yang berbeda.
Pada tahun 1991 World Health Assembly membuat resolusi tentang eliminasi kusta sebagai problem kesehatan masyarakat pada tahun 2000 dengan menurunkan prevalensi kusta menjadi di bawah 1 kasus per 10.000 penduduk. Di Indo- nesia hal ini dikenal sebagai Eliminasi Kusta tahun 2000 (EKT 2000).
Jumlah kasus kusta di seluruh dunia selama 12 tahun terakhir ini telah menurun tajam di sebagian besar negara atau wilayah endemis . Kasus yang terdaftar pada permulaan tahun 2009 tercatat 213.036 penderita yang berasal dari 121 negara, sedangkan jumlah kasus baru tahun 2008 tercatat 249.007. Di Indonesia jumlah kasus kusta yang tercatat permulaan tahun 2009 adalah 21.538 orang dengan kasus baru tahun 2008 sebesar 17.441 orang. Distribusi tidak merata, yang tertinggi antara lain di Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Prevalensi pada tahun 2008 per 10.000 penduduk adalah 0.76.
Kusta merupakan penyakit yang menyeram- kan dan ditakuti , karena dapat terjadi ulserasi , mutilasi, dan deformitas. Penderita kusta bukan menderita karena penyakitnya saja , tetapi juga karena dikucilkan masyarakat sekitarnya . Hal ini akibat kerusakan saraf besar yang ire-versibel di wajah dan ekstremitas, motorik dan sensorik, serta dengan adanya kerusakan yang berulang- ulang pada daerah anestetik disertai paralisis dan atrofi otot.
ETIOLOGI
Kuman penyebab adalah Mycobacterium /eprae yang ditemukan oleh G.A. HANSEN pada tahun 1874 di Norwegia, yang sampai bekarang belum juga dapat dibiakkan dalam media artifisial . M. leprae berbentuk kuman dengan ukuran 3-8μm x 0,5 μm, tahan asam dan alkohol serta positif-Gram.
P A TOGENESIS
Pada tahun 1960 Shepard berhasil meng- inokulasikan M. leprae pada kaki mencit, dan berkembang biak di sekitartempat suntikan . Dari berbagai macam spesimen, bentuk lesi maupun negara asal penderita, ternyata tidak ada per- bedaan spesies. Agar dapat tumbuh diperlukan jumlah minimum M. leprae yang disuntikan dan kalau melampaui j umlah maksimum tidak berarti meningkatkan perkembangbiakan .
lnokulasi pada mencit yang telah diambil timusnya dengan diikuti iradiasi 900 r, sehingga kehilangan respons imun selularnya , akan meng- hasilkan granuloma penuh kuman terutama di bagian tubuh yang relatif dingin , yaitu hidung , cuping telinga, kaki, dan ekor. Kuman tersebut selanjutnya dapat diinokulasikan lagi, berarti me-menuhi salah satu postulat Koch, meskipun be-lum seluruhnya dapat dipenuhi.
Sebenamya M. leprae mempunyai patogenitas dan daya invasi yang rendah, sebab penderita yang mengandung kuman lebih banyak belum tentu memberikan gejala yang lebih berat, bah- kan dapat sebaliknya. Ketidakseimbangan antara derajat infeksi dengan derajat penyakit, tidak lain disebabkan oleh respons imun yang berbeda, yang menggugah timbulnya reaksi granuloma setempat atau menyeluruh yang dapat sembuh sendiri atau progresif. Oleh karena itu penyakit kusta dapat disebut sebagai penyakit imunologik. Gejala klinisnya lebih sebanding dengan tingkat reaksi selularnya daripada intensitasnya infeksinya.
GEJALA KLINIS
Diagnosis penyakit kusta didasarkan gam- baran klinis, bakterioskopis, histopatologis, dan serologis. Di antara ketiganya, diagnosis secara klinislah yang terpenting dan paling sederhana. Hasil bakterioskopis memerlukan waktu paling sedikit 15-30 menit, sedangkan histopatologik 10-14 hari. Kalau memungkinkan dapat dilakukan tes lepromin (Mitsuda) untuk membantu penentuan tipe, yang hasilnya baru dapat diketahui setelah 3 minggu. Penentuan tipe kusta perlu dilakukan agar dapat menetapkan terapi yang sesuai.
Bila kuman M. leprae masuk kedalam tubuh seseorang,dapattimbulgejalaklinissesuaidengan kerentanan orang tersebut. Bentuk tipe klinis bergantung pada sistem imunitas selular (SIS) penderita. Bila SIS baik akan tampak gam-baran klinis ke arah tuberkuloid, sebaliknya SIS rendah memberikan gambaran lepromatosa. Agar proses selanjutnya lebih jelas lihat bagan patogenesis ini (gambar 11-1 ).

Ridley dan Jopling memperkenalkan istilah
spektrum determinate pada penyakit kusta yang
terdiri atas pelbagai tipe atau bentuk, yaitu:
TT : Tuberkuloid polar, bentuk yang stabil
Ti : Tuberkuloid indefinite
BT : Borderline tuberculoid
BB : Mid borderline
BL : Borderline lepromatous
Li : Lepromatosa indefinite
LL : Lepromatosa polar, bentuk yang stabil
Tipe I (indeterminate) tidak termasuk dalam
spektrum. TT adalah tipe tuberkuloid polar, yakni
tuberkuloid 100%, merupakan tipe yang stabil, jadi berarti tidak mungkin berubah tipe. Begitu
jugaLL adalah tipe lepromatosapolar, yakni
lepromatosa 100%, juga merupakan tipe yang
stabil yang tidak mungkin berubah lagi. Sedang-
kan tipe antara Ti dan Li disebut tipe borderline atau
campuran, berarti campuran antara tuberkuloid dan
lepromatosa. BB adalah tipe campuran yang ter-
diri atas 50% tuberkuloid dan 50% lepromatosa.
BT dan Ti lebih banyak tuberkuloidnya, sedang
BLdan Li lebih banyak lepromatosanya. Tipe-tipe
campuran ini adalah tipe yang labil, berarti dapat
bebas beralih tipe, baik ke arah TI maupun ke
arah LL. Zona spektrum kusta menurut berbagai
klasifikasi dapat dilihat pada tabel 11-1.

Multibasilar berarti mengandung banyak kuman
yaitu tipe LL, BL dan BB . Sedangkan pausibasilar
berarti mengandung sedikit kuman, yakni tipe
TT, BT, dan I. Diagnosis banding berbagai tipe
tersebut tercantum pada tabel 11-2 dan 11-3.
Menurut WHO pada tahun 1981, kusta
dibagi menjadi multibasilar dan pausibasilar. Yang
termasuk dalam multibasilar adalah tipe LL, BL dan
BB pada klasifikasi Ridley-Jopling dengan indeks
Bakteri (IB) lebih dari 2+ sedangkan pausibasilar
adalah tipe I, T I dan BT dengan IB kurang dari 2+ .
Untuk kepentingan pengobatan pada tahun
1987 telah te~adi perubahan klasifikasi. Yang
dimaksud dengan kusta PB adalah kusta dengan
BTA negatif pada pemeriksaan kerokan jaringan
kulit, yaitu tipe-tipe I, T I dan BT menurut klasifikasi
Ridley- Jopling.

Bila pada tipe-tipe tersebut disertai STA positif,
maka akan dimasukkan ke dalam kusta MB.
Sedangkan kusta MB adalah semua penderita
kusta tipe BB, BL dan LL atau apa pun klasifikasi
klinisnya dengan STA positif, harus diobati dengan
rejimen MDT-MB.
Karena pemeriksaan kerokan jaringan kulit
tidak selalu tersedia di lapangan , pada tahun 1995
WHO lebih menyederhanakan klasifikasi klinis
kusta berdasarkan hitung lesi kulit dan saraf
yang terkena. Hal ini tercantum pada tabel 11-4.
Antara diagnosis secara klinis dan secara
histopatologik, ada kemungkinan terdapat
persamaan maupun perbedaan tipe . Perlu
diingat bahwa diagnosis klinis seseorang harus
didasarkan hasil pemeriksaan kelainan klinis
seluruh tubuh orang tersebut. Sebaiknya jangan
hanya didasarkan pemeriksaan sebagian tubuh
saja, sebab ada kemungkinan diagnosis klinis di
wajah berbeda dengan tubuh , lengan , tungkai ,
dan sebagainya . Bahkan pada satu lesi (kelainan
kulit) pun dapat berbeda tipenya , umpamanya di
sisi kiri berbeda dengan sisi kanan. Begitu pula
dasar diagnosis histopatologik, tergantung pada
beberapa tempat dan dari tempat mana biopsi-
nya diambil. Sebagaimana lazimnya dalam ben-
tuk diagnosis klinis, dimulai dengan inspeksi,
palpasi, lalu dilakukan pemeriksaan yang meng-
gunakan alat sederhana, yaitu: jarum, kapas,
tabung reaksi masing-masing dengan air panas
dan air dingin, pensil tinta, dan sebagainya.
Kusta terkenal sebagai penyakit yang paling
ditakuti karena deformitas atau cacat tubuh
Orang awam pun dengan mudah dapat menduga
ke arah penyakit kusta. Yang penting bagi kita
sebagai dokter dan ahli kesehatan lainnya,
bahkan barangkali para ahli kecantikan dapat
menduga ke arah penyakit kusta, terutama bagi
kelainan kulit yang masih berupa makula hipo-
pigmentasi , hiperpigmentasi dan eritematosa.
Kelainan kulit pada penyakit kusta tanpa
komplikasi dapat hanya berbentuk makula saja ,
infitrat saja, atau keduanya. Buatlah diagnosis
banding dengan banyak penyakit kulit lainnya
yang hampir serupa, sebab penyakit kusta ini
mendapat ju lukan the greatest imitator dalam
ilmu Penyakit Kulit. Penyakit kulit yang harus
diperhatikan sebagai diagnosis banding antara
lain dermatofitosis, tinea versikolor, pitiriasis
rosea, pitiriasis alba, dermatitis seboroika ,
psoriasis , neurofibromatosis , granula anulare ,
xantomatosis , skleroderma , leukemia kutis,
tuberkulosis kutis verukosa, dan birth mark.
Kalau secara inspeksi mirip penyakit
lain, ada tidaknya anestesia sangat banyak
membantu penentuan diagnosis , meskipun
tidak selalu jelas. Hal ini dengan mudah dilakukan
dengan menggunakan jarum terhadap rasa nyeri,
kapas terhadap rasa raba dan kalau masih belum
jelasdengankeduacaratersebutbarulahpengujian
terhadaprasasuhu,yaitupanasdandingindengan
menggunakan 2 tabung reaksi.
Untuk mengetahui adanya kerusakan fungsi
saraf otonom perhatikan ada tidaknya dehidrasi di
daerah lesi yang dapat jelas dan dapat pula tidak,
yang dipertegas menggunakan pensil tinta
(tanda Gunawan). Cara menggoresnya mulai
dari tengah lesi ke arah kulit normal. Bila ada
gangguan, goresan pada kulit normal akan lebih
tebal bila dibandingkan dengan bagian tengah
lesi. Dapat pula diperhatikan adanya alopesia di
daerah lesi, yang kadang-kadang dapat mem-
bantu, tetapi bagi penderita yang memiliki kulit
berambut sedikit, sangat sukar menentukannya.
Gangguan fungsi motoris diperiksa dengan
Voluntary Muscle Test (VMT).
Mengenai saraf perifer yang perlu diperhati-
kan ialah pembesaran , konsistensi, ada/tidaknya
nyeri spontan dan/atau nyeri tekan. Hanya bebe-
rapa saraf superfisial yang dapat dan perlu di-
periksa, yaitu N. fasialis, N. aurikularis magnus, N.
radialis, N. ulnaris, N. medianus, N. politea lateralis,
dan N. tibialis posterior. Tampaknya mudah,
tetapi memerlukan latihan dan kebiasaan untuk
memeriksanya . Bagi tipe ke arah lepromatosa
kelainan saraf biasanya bilateral dan menyeluruh,
sedang bagi tipe tuberkuloid, kelainan sarafnya
lebih terlokalisasi mengikuti tempat lesinya.
Deformitas atau cacat kusta sesuai dengan
patofisiologinya , dapat dibagi dalam deformitas
primer dan sekunder. Deformitas primer sebagai
akibat langsung oleh granuloma yang terbentuk
sebagai reaksi terhadap M. leprae, yang men-
desak dan merusak jaringan di sekitarnya, yaitu
kulit, mukosa traktus respiratorius alas, tulang-
tulang jari , dan wajah . Deformitas sekunder
terjadi sebagai akibat adanya deformitas primer,
terutama kerusakan saraf (sensorik, motorik,
otonom), antara lain kontraktur sendi, mutilasi
tangan dan kaki.
PENUNJANG DIAGNOSIS
1. Pemeriksaan bakterioskopik (kerokan
jaringan kulit)
Pemeriksaan bakterioskopik digunakan
untuk membantu menegakkan diagnosis dan
pengamatan pengobatan . Sediaan dibuat
dari kerokan jaringan kulit atau usapan dan
kerokan mukosa hidung yang diwamai dengan pewarnaan terhadap basil tahan asam
(ST A) , antara lain dengan ZIEHL-NEELSEN .
Bakterioskopik negatif pada seorang pen-
derita, bukan berarti orang tersebut tidak
mengandung kuman M. leprae.
Pertama-tama harus ditentukan lesi
di kulit yang diharapkan paling padat oleh
kuman , setelah terlebih dahulu menentukan
jumlah tempat yang akan diambil. Mengenai
jumlah lesi juga ditentukan oleh tujuannya,
yaitu untuk riset atau rutin . Untuk riset dapat
diperiksa 10 tempat dan untuk rutin sebaik-
nya minimal 4-6 tempat, yaitu kedua cuping
telinga bagian bawah dan 2-4 lesi lain yang
paling aktif, berarti yang paling eritema-
tosa dan paling infiltratif. Pemilihan kedua
cuping telinga tersebut tanpa menghiraukan
ada tidaknya lesi di tempat tersebut, oleh
karena atas dasar pengalaman tempat
tersebut diharapkan mengandung kuman
paling banyak. Perlu diingat bahwa setiap
tempat pengambilan harus dicatat, guna
pengambilan ditempat yang sama pada
pengamatan pengobatan untuk dibanding-
kan hasilnya.
Cara pengambilan bahan dengan meng-
gunakan skalpel steril. Setelah lesi tersebut
didesinfeksi kemudian dijepit antara ibu
jari dan jari telunjuk agar menjadi iskemik,
sehingga kerokan jaringan mengandung
sedikit mungkin darah yang akan meng-
ganggu gambaran sediaan . lrisan yang
dibuat harus sampai di dermis, melampaui
subepidermal clear zone agar mencapai
jaringan yang diharapkan banyak mengan-
dung sel Virchow (sel lepra) yang di dalam-
nya mengandung kuman M. leprae. Kerokan
jaringan itu dioleskan di gelas alas, difiksasi
di atas api, kemudian diwamai dengan
pewamaan yang klasik, yaitu Ziehl Neelsen.
Untuk pewarnaan ini dapat digunakan
modifikasi Ziehl Neelsen dan cara-cara lain
dengan segala kelebihan dan kekurangan-
nya disesuaikan dengan keadaan setempat.
Sediaan mukosa hidung diperoleh dengan
cara nose blows, terbaik dilakukan pagi hari
yang ditampung pada sehelai plastik. Per-
hatikan sifat duh tubuh (discharge) tersebut,
apakah cair, serosa, bening , mukoid , muko-
purulen , purulen, ada darah atau tidak.
Sediaan dapat dibuat langsung atau plastik
tersebut dilipat dan kirim ke laboratorium.
2. Pemeriksaan histopatologik
Makrofag dalam jaringan yang berasal
dari monosit di dalam darah ada yang
mempunyai nama khusus , antara lain sel
Kupffer dari hati, sel alveolar dari paru, sel
glia dari otak, dan yang dari kulit disebut
histiosit. Salah satu tugas makrofag adalah
melakukan fagositosis. Kalau ada kuman (M.
/eprae) masuk, akibatnya akan bergantung
pada Sistem lmunitas Selular (SIS) orang
itu. Apabila SIS-nya tinggi, makrofag akan
mampu memfagosit M. leprae . Datangnya
histiosit ke tempat kuman disebabkan karena
proses imunologik dengan adanya faktor
kemotaktik. Kalau berlebihan dan tidak ada
lagi yang harus difagosit, makrofag akan
berubah bentuk menjadi sel epiteloid yang
tidak dapat bergerak dan kemudian akan
dapat berubah menjadi sel datia Langhans.
Adanya massa epiteloid yang berlebihan
dikelilingi oleh limfosit yang disebut tuberkel
akan menjadi penyebab utama kerusakan
jaringan dan cacat. Pada penderita dengan
SIS rendah atau lumpuh, histiosit tidak dapat
menghancurkan M. leprae yang sudah
ada didalamnya, bahkan dijadikan tempat
berkembang biak dan disebut sel Virchow
atau sel lepra atau sel busa dan sebagai alat
pengangkutpenyebarluasan .
Granuloma adalah akumulasi makrofag
dan atau derivat-derivatnya. Gambaran histo-
patologik tipe tuberkuloid adalah tuberkel dan
kerusakan saraf yang lebih nyata, tidak ada
kuman atau hanya sedikit dan non-solid. Pada
tipe lepromatosa terdapat kelim sunyi sub-
epidermal (subepidermal clear zone), yaitu
suatu daerah langsung di bawah epidermis
yang jaringannya tidak patologik. Didapati sel
Virchow dengan banyak kuman. Pada tipe borderline , terdapat campuran
tersebut
3. Pemeriksaan serologik
Pemeriksaan serologik kusta didasarkan
atas terbentuknya antibodi pada tubuh
seseorang yang terinfeksi oleh M. leprae.
Antibodi yang terbentuk dapat bersifat
spesifik terhadap M. leprae, yaitu antibodi
anti phenolic glycolipid-1 (PGL-1) dan
antibodi antiprotein 16 kD serta 35 kD.
Sedangkan antibodi yang tidak spesifik
antara lain antibodi anti-lipoarabinomanan
(LAM), yang juga dihasilkan oleh kuman M.
tuberculosis.
Kegunaan pemeriksaan serologik ini ialah
dapat membantu diagnosis kusta yang meragu-
kan, karena tanda klinis dan bakteriologik tidak
jelas. Di samping itu dapat membantu menentu-
kan kusta subklinis, karena tidak didapati lesi kulit,
misalnya pada narakontak serumah. Macam-
macam pemeriksaan serologik kusta ialah:
- Uji MLP A (Mycobacterium Leprae Particle
Aglutination)
Uji ELISA (Enzyme Linked lmmunosorbent
Assay)
ML dipstick test (Mycobacterium leprae
dipstick)
ML flow test (Mycobacterium leprae flow test)
REAKSIKUSTA
Reaksi kusta adalah interupsi dengan
episode akut pada perjalanan penyakit yang
sebenarnya sangat kronik. Adapun patofisiologi
belum jelas betul, terminologi dan klasifikasi masih
bermacam-macam. Mengenai patofisiologinya
yang belum jelas tersebut akan dijelaskan secara
imunologik. Reaksi imun dapat menguntungkan,
tetapi dapat pula merugikan yang disebut reaksi
imun patologik, dan reaksi kusta ini tergolong di-
dalamnya. Dalam klasifikasi yang bermacam-
macam itu, yang tampaknya paling banyak dianut
pada akhir-akhir ini, yaitu:
ENL (eritema nodusum leprosum) dan
Reaksi reversal atau reaksi upgrading
Secara imunopatologis, ENL termasuk
respons imun humoral, berupa fenomena
kompleks imun akibat reaksi antara antigen M.
leprae + antibodi (lgM, lgG) + komplemen ~
kompleks imun.
Tampaknya reaksi ini analog dengan reaksi
fenomena unik, tidak dapat disamakan begitu
saja dengan penyakit lain. Dengan terbentuknya
kompleks imun ini, maka ENL termasuk di dalam
golongan penyakit kompleks imun, oleh karena
salah satu protein M. leprae bersifat antigenik,
maka antibodi dapat terbentuk. Temyata bahwa
kadar imunoglobulin penderita kusta lepromatosa
lebih tinggi daripada tipe tuberkuloid . Hal ini te~adi
oleh karena pada tipe lepromatosa jumlah kuman
jauh lebih banyak daripada tipe tuberkuloid.
ENL lebih banyak terjadi pada pengobatan
tahun kedua. Hal ini dapat te~adi karena pada
pengobatan, banyak kuman kusta yang mati dan
hancur, berarti banyak antigen yang dilepaskan
dan bereaksi dengan antibodi, serta mengaktifkan
sistem komplemen. Kompleks imun tersebut terus
beredar dalam sirkulasi darah yang akhirnya dapat
melibatkan berbagai organ.
Pada kulit akan timbul gejala klinis yang
berupa nodus eritema, dan nyeri dengan tempat
predileksi di lengan dan tungkai. Bila mengenai
organ lain dapat menimbulkan gejala seperti irido-
siklitis, neuritis akut, limfadenitis, artritis, orkitis, dan
nefritis akut dengan adanya proteinuria. ENL dapat disertai gejala konstitusi dari ringan sampai berat
yang dapat diterangkan secara imunologik pula.
Perlu ditegaskan bahwa pada ENL tidak
terjadi perubahan tipe. Lain halnya dengan reaksi
reversal yang hanya dapat terjadi pada tipe
borderline (Li, BL, BB, BT, Ti), sehingga dapat di-
sebut reaksi borderline. Yang memegang peranan
utama dalam hal ini adalah SIS, yaitu terjadi
peningkatan mendadak SIS. Meskipun faktor pen-
cetusnya belum diketahui pasti , diperkirakan ada
hubungannya dengan reaksi hipersensitivitas tipe
lambat. Reaksi peradangan terjadi pada tempat-
tempat kuman M. leprae berada, yaitu pada saraf
dan kulit, umumnya terjadi pada pengobatan 6
bulan pertama. Neuritis akut dapat menyebabkan
kerusakan saraf secara mendadak, oleh karena itu
memerlukan pengobatan segera yang memadai.
Seperti pemah diterangkan terdahulu bahwa yang
menentukan tipe penyakit adalah SIS. Tipe kusta
yang termasuk borderline ini dapat bergerak bebas
ke arah T I dan LL dengan mengikuti naik turunnya
SIS, sebab setiap perubahan tipe selalu disertai
perubahan SIS pula. Begitu pula reaksi reversal,
terjadi perpindahan tipe ke arah T I dengan disertai
peningkatan SIS , hanya bedanya dengan cara
mendadak dan cepat.
Penggunaan istilah downgrading untuk reaksi
kusta, akhir-akhir ini sudah hampir tidak terdengar
lagi, tetapi pemakaiannya hanya untuk menunjuk-
kan pergeseran ke arah lepromatosa masih tetap
berlaku, berarti bergerak secara lambat, tidak
secepat reaksi.
Gejala klinis reaksi reversal ialah umumnya
sebagian atau seluruh lesi yang telah ada bertambah
aktif dan atau timbul lesi baru dalam waktu yang
relatif singkat. Artinya lesi hipopigmentasi menjadi
eritema, lesi eritema menjadi makin eritematosa, lesi
makula menjadi infiltrat, lesi infiltrat makin infiltratif
dan lesi lama menjadi bertambah luas. Tidak perlu
seluruh gejala harus ada, satu saja sudah cukup.
Adanya gejala neu-ritis akut penting diperhatikan,
karena sangat menentukan pemberian pengobatan
kortikosteroid, sebab tanpa gejala neuritis akut
pemberian kortikosteroid adalah fakultatif.
Kalau diperhatikan kembali reaksi ENL dan
reversal secara klinis, ENL dengan lesi eritema
nodosum sedangkan reversal tanpa nodus, se-
hingga disebut reaksi lepra nodular, sedangkan
reaksi reversal adalah reaksi non-nodular. Hal ini
penting membantu menegakkan diagnosis reaksi atas dasar lesi, ada atau tidak adanya nodus.
Kalau ada berarti reaksi nodular atau ENL, jika
tidak ada berarti reaksi non-nodular atau reaksi
reversal atau reaksi borderline.
PENGOBATAN KUSTA
Obat antikusta yang paling banyak dipakai
pada saat ini adalah DDS {diaminodifenil sulfon)
kemudian klofazimin, dan rifampisin. DDS mulai
dipakai sejak 1948 dan di Indonesia digunakan
pada tahun 1952. Klofazimin dipakai sejak 1962
oleh BROWN dan HOGERZEIL, dan rifampisin
sejak tahun 1970. Pada tahun 1998 WHO me-
nambahkan 3 obat antibiotik lain untuk peng-
obatan alternatif, yaitu ofloksasin, minosiklin dan
klaritromisin .
Untuk mencegah resistensi, pengobatan
tuberkulosis telah menggunakan multi drug
treatment (MDT) sejak 1951, sedangkan untuk
kusta baru dimulai pada tahun 1971.
Pada saat ini ada berbagai macam dan
cara MDT dan yang dilaksanakan di Indonesia
sesuai rekomendasi WHO, dengan obat alternatif
sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan.
Yang paling dirisaukan ialah resistensi terhadap
DDS, karena DDS adalah obat antikusta yang
paling banyak dipakai dan paling murah. Obat ini
sesuai dengan para penderita yang ada di negara
berkembang dengan sosial ekonomi rendah.
MDT digunakan sebagai usaha untuk:
mencegah dan mengobati resistensi
memperpendek masa pengobatan
mempercepat pemutusan mata rantai pe-
nularan
Untuk menyusun kombinasi obat perlu
diperhatikan antara lain:
efek terapeutik obat
efek samping obat
ketersediaan obat
harga obat
kemungkinan penerapannya
DDS
Tentang sejarah pemakaian DDS, pada 20
tahun pertama digunakan sebagai monoterapi.
Pada tahun 1960, Shepard berhasil melakukan
inokulasi M. leprae ke dalam telapak kaki mencit.
Pada tahun 1964, pembuktian pertama kali dengan inokulasi adanya resistensi terhadap DDS
oleh Pettit dan Rees, disusul secara beruntun
pembuktian adanya resistensi yang meningkat
di berbagai negara . Dengan adanya pembuktian
resistensi tersebut berubahlah pola berpikir dan
tindakan kemoterapi kusta dari monoterapi ke
MDT.
Pengertian relaps atau kambuh pada kusta
ada 2 kemungkinan , yaitu relaps sensitif (persisten)
dan relaps resisten. Pada relaps sensitif penyakit
kambuh setelah menyelesaikan pengobatan se-
suai dengan waktu yang ditentukan. Secara klinis,
bakterioskopik, histopatologik dapat dinyatakan
penyakit tiba-tiba aktif kembali dengan timbulnya
lesi baru dan bakterioskopik positif kembali. Tetapi
setelah dibuktikan dengan pengobatan dan
inokulasi pada mencit, ternyata M. leprae masih
sensitif terhadap DDS. M. leprae yang semula
dorman, sleeping, atau persisten, bangun dan
aktif kembali . Pada pengobatan sebelumnya,
kuman dorman sukar dihancurkan dengan obat
atau MDT apapun . Pada relaps resisten penyakit
kambuh setelah menyelesaikan pengobatan
sesuai dengan waktu yang ditentukan, tetapi
tidak dapat diobati dengan obat yang sama.
Dengan gejala klinis, bakterioskopik, dan histo-
patologik yang khas, dapat dibuktikan dengan
percobaan pengobatan dan inokulasi pada
mencit, bahwa M. leprae resisten terhadap DDS.
Cara pembuktiannya ialah dengan percobaan
pengobatan dengan DDS 100 mg sehari selama
3 bulan sampai 6 bulan disertai pengamatan
secara klinis, bakterioskopik, dan histopatologik.
Apabila fasilitas mengizinkan, dapat ditentukan
gradasi resistensinya dari yang rendah,sedang,
sampa i yang tinggi. lnokulasi mencit pernah
dilaksanakan di Bagian Mikrobiologi FKUI
Jakarta.
Resistensi hanya terjadi pada kusta multi-
basi lar, tetapi tidak pada pausibasilar oleh karena
SIS penderita PB tinggi dan pengobatannya relatif
singkat. Resistensi terhadap DDS dapat primer
maupun sekunder. Resistensi primer, terjadi bila
orang ditulari oleh M. leprae yang telah resisten,
dan manifestasinya dapat dalam berbagai tipe
(TT, BT, BB , BL , LL) , bergantung pada SIS
penderita. Derajat resistensi yang rendah masih
dapat diobati dengan dosis DDS yang lebih
tinggi, sedangkan pada derajat resistensi yang
tinggi DDS tidak dapat dipakai lagi.
Resistensi sekunder terjadi oleh karena:
-monoterapi DDS
-dosis terlalu rendah
-minum obat tidak teratur
-minum obat tidak adekuat, baik dosis maupun
lama pemberiannya
-pengobatan terlalu lama, setelah 4-24 tahun
Efek samping DDS antara lain nyeri kepala,
erupsi obat , anemia hemolitik , leukopenia ,
insomnia, neuropati perifer, sindrom DDS, nekro-
lisis epidermal toksik, hepatitis, hipoalbuminemia,
dan methemoglobinemia.
Rifampisin
Rifampisin adalah obat yang menjadi salah
satu komponen kombinasi DDS dengan dosis
10 mg/kg berat badan ; diberikan setiap hari atau
setiap bulan. Rifampisin tidak boleh diberikan
sebagai monoterapi, oleh karena memperbesar
kemungkinan terjadinya resistensi, tetapi pada
pengobatan kombinasi selalu diikutkan , tidak
boleh diberikan setiap minggu atau setiap 2
minggu mengingat efek sampingnya.
Ditemukan dan dipakai sebagai obat anti-
tuberkulosis pada tahun 1965 dan sebagai obat
kusta pada tahun 1970 oleh Rees dkk., serta
Leiker dan Kamp. Resistensi pertama terhadap
M. leprae dibuktikan pada tahun 1976 oleh
Jacobson dan Hastings.
Efek samping yang harus diperhatikan adalah
hepatotoksik, nefrotoksik, gejala gastrointestinal,
flu-like syndrome, dan erupsi kulit.
Klofazimin (lampren)
Obat ini mulai dipakai sebagai obat kusta
pada tahun 1962 oleh Brown dan Hoogerzeil.
Dosis sebagai antikusta ialah 50 mg setiap
hari, atau 100 mg selang sehari, atau 3 x 100
mg setiap minggu . Juga bersifat antinflamasi
sehingga dapat dipakai pada penanggulangan
ENL dengan dosis lebih yaitu 200 mg-300 mg/
hari namun awitan kerja baru timbul setelah 2-3
minggu . Resistensi pertama pada satu kasus
dibuktikan pada tahun 1982.
Efek sampingnya ialah warna merah ke-
coklatan pada kulit, dan warna kekuningan pada
sklera , sehingga mirip ikterus , apalagi pada
dosis tinggi , yang sering merupakan masalah
dalam ketaatan berobat penderita. Hal tersebut
disebabkan karena klofazimin adalah zat warna
dan dideposit terutama pada sel sistem retikulo-
endotelial, mukosa dan kulit. Pigmentasi bersifat reversibel , meskipun menghilangnya lambat sejak
obat dihentikan. Efek samping lain yang hanya
terjadi dalam dosis tinggi, yakni nyeri abdomen,
nausea, diare, anoreksia, dan vomitus. Selain itu
dapat terjadi penurunan berat badan.
Protionamid
Dosis diberikan 5-10 mg/kg berat badan setiap
hari, dan untuk Indonesia obat ini tidak atau jarang
dipakai. Distribusi protionamid dalam jaringan tidak
merata, sehingga kadar hambat minimalnya sukar
ditentukan .
Obat alternatif
Ofloksasin
Ofloksasin merupakan turunan fluorokuinolon
yang paling aktif terhadap Mycobacterium leprae
in vitro. Dosis optimal harian adalah 400 mg .
Dosis tunggal yang diberikan dalam 22 dosis akan
membunuh kuman Mycobacterium leprae hidup
sebesar 99,99%. Efek sampingnya adalah mual,
diare, dan gangguan saluran cema lainnya, ber-
bagai gangguan susunan saraf pusat termasuk
insomnia, nyeri kepala, dizziness, nervousness
dan halusinasi. Walaupun demikian hal ini jarang
ditemukan dan biasanya tidak membutuhkan
penghentian pemakaian obat.
Penggunaan pada anak, remaja, ibu hamil
dan menyusui harus hati-hati, karena pada hewan
muda, kuinolon menyebabkan artropati.
Minosiklin
Termasuk dalam kelompok tetrasiklin. Efek
bakterisidalnya lebih tinggi daripada klaritromisin ,
tetapi lebih rendah daripada rifampisin. Dosis
standar harian 100 mg. Efek sampingnya adalah
pewarnaan gigi bayi dan anak-anak, kadang-
kadang menyebabkan hiperpigmentasi kulit dan
membran mukosa, berbagai simtom saluran cema
dan susunan saraf pusat, termasuk dizziness dan
unsteadiness. Oleh sebab itu tidak dianjurkan
untuk anak-anak atau selama kehamilan.
Cara pemberian MDT
1. MDT untuk multibasilar (BB, BL, LL, atau
semua tipe dengan BTA positif) adalah:
- Rifampisin 600 mg setiap bulan , dalam pe-
ngawasan
- DDS 100 mg setiap hari
- Klofazimin: 300 mg setiap bulan, dalam pe-
ngawasan , diteruskan 50 mg sehari atau
100 mg selama sehari atau 3 kali 100 mg
setiap minggu
Awalnya kombinasi obat ini diberikan 24 dosis
dalam 24 sampai 36 bulan dengan syarat bakte-
rioskopis harus negatif. Apabila bakterioskopis
masih positif, pengobatan harus dilanjutkan sampai
bakterioskopis negatif. Selama pengobatan dilaku-
kan pemeriksaan secara klinis setiap bulan dan
secara bakterioskopis minimal setiap 3 bulan .
Jadi besar kemungkinan pengobatan kusta multi-
basilar ini hanya selama 2 sampai 3 tahun. Hal
ini adalah waktu yang relatif sangat singkat dan
dengan batasan waktu yang tegas, jika dibanding-
kan dengan cara sebelumnya yang memerlukan
waktu minimal 10 tahun sampai seumur hidup.
Penghentian pemberian obat lazim disebut Release
From Treatment (RFT). Setelah RFT dilakukan
tindak lanjut (tanpa pengobatan) secara klinis
dan bakterioskopis minimal setiap tahun selama
5 tahun. Kalau bakterioskopis tetap negatif dan
klinis tidak ada keaktifan baru, maka dinyatakan
bebas dari pengamatan atau disebut Release From
Control (RFC).
Saat ini, apabila secara klinis sudah terjadi
penyembuhan, pemberian obat dapat dihentikan ,
tanpa memperhatikan bakterioskopis.
Pencegahan cacat
Penderita kusta yang terlambat didiagnosis
dan tidak mendapat MDT mempunyai risiko
tinggi untuk te~adinya kerusakan saraf. Selain itu,
penderita dengan reaksi kusta, terutama reaksi reversal , lesi kulit multipel dan dengan saraf yang
membesar atau nyeri juga memiliki risiko tersebut.
Kerusakan saraf terutama berbentuk
nyeri saraf, hilangnya sensibilitas dan
berkurangnya kekuatan otot. Penderitalah
yang mula-mula menyadari adanya
perubahan sensibilitas atau kekuatan otot.
Keluhan berbentuk nyeri saraf atau Iuka
yang tidak sakit, lepuh kulit atau hanya ber-
bentuk daerah yang kehilangan sensibilitas-
nya saja. Juga ditemukan keluhan sukarnya
melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya
memasang kancing baju, memegang
pulpen atau mengambil benda kecil , atau
kesukaran berjalan. Semua keluhan tersebut
harus diperiksa dengan teliti dengan
anamnesis yang baik tentang bentuk dan
lamanya keluhan , sebab pengobatan dini
dapat mengobati, sekurangnya mencegah
kerusakan menjadi berlanjut.
Cara terbaik untuk melakukan pencegahan
cacat atau prevention of disabilities (POD)
adalah dengan melaksanakan diagnosis
dini kusta, pemberian pengobatan MDT
yang cepat dan tepat. Selanjutnya dengan
mengenali gejala dan tanda reaksi kusta
yang disertai gangguan saraf serta memulai
pengobatan dengan kortikosteroid sesegera
mungkin . Bila terdapat gangguan sensibilitas,
penderita diberi petunjuk sederhana misalnya
memakai sepatu untuk melindungi kaki yang
telah terkena, memaka i sarung tangan
bila bekerja dengan benda yang tajam
atau panas, dan memakai kacamata untuk
melindungi matanya. Selain itu diajarkan
pula cara perawatan kulit sehari-hari. Hal
ini dimulai dengan memeriksa ada tidaknya
memar, Iuka, atau ulkus. Setelah itu tangan
dan kaki direndam , disikat dan dimi-nyaki
agar tidak kering dan pecah.
WHO Expert Committee on Leprosy
(1977) membuat klasifikasi cacat bagi
penderita kusta . Pada pertemuan yang
ketujuh dibuat amandemen khusus untuk
mata
Rehabilitasi
Usaha rehabilitasi medis yang dapat dilaku-
kan untuk cacat tubuh ialah antara lain dengan
jalan operasi dan fisioterapi. Meskipun hasilnya
tidak sempuma kembali ke asal, tetapi fungsinya
dan secara kosmetik dapat diperbaiki.
Cara lain ialah secara kekaryaan, yaitu mem-
beri lapangan pekerjaan yang sesuai cacat tubuh-
nya, sehingga dapat berprestasi dan dapat meningkatkan rasa percaya diri, selain itu dapat dilakukan
terapi psikologik (kejiwaan).
DAFTAR PUSTAKA
1. Agusni I, Menaldi SL. Beberapa prosedur diagnosis
baru pada penyakit kusta. Dalam: Syamsoe Daili ES,
Menaldi SL, lsmiarto SP, Nilasari H, editor. Kusta.
Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 2003. h. 59-65.
2. BrycesonA,PfaltzgraffRE. Leprosy.31<1ed.Edinburg:
Chruchill Livingstone; 1990.
3. Hastings RC. Leprosy. Edinburg : Churchill Living-
stone; 1985.
4. World Health Organization. A guide to eliminating
leprosy as a public health problem. 1•1ed. Geneva:
WHO; 1995.
5. World Health Organization . WHO model pre-
scribing infonnation. Drug used in leprosy. Geneva:
WHO; 1998.
6. Kumar H, Kumar B. IAL Textbook of Leprosy. 1•1 ed.
New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd;
2010.
7 . Elston OM, Berger TG, James WO . Hansen;s
Disease. In: Andrew's diseases of the skin. Clinical
Dennatology. 10., ed. Philadelphia: WB Saunders
Company; 2006. p. 343-52.
8. Modlin RL, Rea TH, Lee DJ, Weinberg AN. Leprosy.
In: Fitzpatrick TB, Eisen AZ., Wolff K, Freedberg IM,
Austen KF. Dennatology in General Medicine. 8., ed.
New York: McGraw-Hill Book Company; 2012. p.
2253-62.